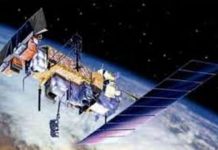Jakarta, KomITe.ID – Kemajuan teknologi informasi yang berlanjut dengan pesatnya perkembangan teknologi data merupakan keniscayaan yang mengubah peta ekonomi dan politik dunia. Ancaman geopolitik, pertahanan dan keamanan pun berubah. Hancurnya ibu kota ISIS di Mosul, karena serangan pasukan koalisi bersama Irak, menjadikan perang global melawan ISIS pun berubah dari perang kota konvensional menjadi perang proxy dan asimetris. Hal ini disebabkan menyebarnya para milisi ISIS ke arah Asia, seperti beberapa waktu lalu dimana kalangan kaum radikal melakukan teror di kota Marawi, Filiphina. Sangat mungkin, kejadian serupa akan terjadi di berbagai negara seperti Afghanistan, Malaysia, Thailand atau Indonesia.
Menghadapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo sudah memberi perhatian tentang pentingnya antisipasi perubahan visi dan strategi di bidang pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang disampaikan kepada 728 calon perwira remaja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia (Polri) di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, 24 Juli tahun lalu, Presiden menekankan perlunya diadakan alat utama sistim pertahanan ke arah yang berbasis teknologi drone.
Tugas dan landscape perang masa depan yang berbeda dengan masa lalu ini nampaknya mengharuskan teknologi virtual video warfare menjadi pilihan utama. Teknologi ini sangat dimungkinkan untuk dapat mengantisipasi perang proxy yang bersifat asimetris, terutama untuk menghadapi perang cyber. Maka sangat tepat bila Presiden Jokowi berharap para perwira remaja kelak mampu menguasai teknologi informasi beserta analisis teknologi datanya.
Seperti kita pahami bersama, di masa depan perang bukan lagi memperebutkan wilayah atau komoditas yang berasal dari sumber daya manusia atau alam. Namun komoditasnya sudah bergeser ke teror melalui paham ideologi dan narkoba. Infrastrukturnya pun juga sudah memakai teknologi informasi, data informasi, dunia hitam Cyber, Dark dan Deep Web (Komite.id:10/2017), serta media sosial sebagai media komunikasinya.
Melalui media sosial inilah penyebaran paham radikal di Indonesia bergerak cepat dan bebas meski berbagai satuan pengamanan cyber telah bekerja dengan keras. Perekrutan para calon ‘pengantin’, istilah untuk melakukan bom bunuh diri, juga dilakukan melalui medium media sosial ini. Sangat mungkin, melalui teknologi data yang mereka miliki, para elit ISIS telah mampu memetakan daerah-daerah yang kondisi sosialnya tidak kondusif serta memiliki komunitas yang ‘merasa’ keadilan sudah tidak lagi mereka dapatkan.
ERA POST-TRUTH
Kekuatan media sosial memang sudah menunjukkan keampuhannya. Informasi yang berdasarkan fakta dan informasi palsu alias hoax sudah sulit dibedakan. Tahun 2016, kamus Oxford, yang memfokuskan pada bahasa atau kata modern yang kerap digunakan publik, menyebutkan bahwa informasi palsu atau hoax menjadi hal yang populer di tahun itu. Hoax yang terus-menerus dilakukan secara sistemik inilah yang kemudian mampu mengalahkan fakta dan kemudian melahirkan istilah post-truth.
Post-truth, dalam difinisinya adalah kondisi di mana fakta tidak berpengaruh lagi dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Singkatnya, orang tidak lagi mempercayai fakta, mereka lebih meyakini keyakinan mereka atas suatu informasi yang datang dari orang yang menurutnya layak untuk dipercaya dan dihormati. Dan di era post-truth inilah yang kemudian menjadi eranya kebenaran tak lagi dipercaya serta membuat perilaku serta keyakinan orang berubah.
Fenomena post-truth akibat maraknya media sosial menjadi relevan di Indonesia. Pidato dan pesan para elit ISIS nun jauh di jazirah Arab yang menebar ideologi kekerasan dan kebencian misalnya, diterima sebagian masyarakat kita sebagai pesan moral ulama agung yang mesti diperjuangkan meski kematian menjadi taruhannya. Jalan pintas menuju sorga setelah melakukan jihad dengan bunuh diri menjadi iming-iming yang menjanjikan daripada hidup penuh kekalahan dan melelahkan. Fenomena post-truth negatif dan menghasut ini harus bisa segera difilter dari media sosial jika tidak ingin indoktrinasi kekerasan ini menimbulkan masalah pada kedaulatan negara kita.
Hipotesa riset Haroon Ullah, dosen tamu di School of Foreign Service George Town University mengenai motif seseorang menjadi religious extremist sampai mau menjadi calon pembawa bom bunuh diri atau ‘pengantin’, adalah Poverty (garis kemiskinan) dan Ignorance (garis kebodohan). Garis kemiskinan bekerja menggerogoti orang miskin (the poor) hingga tampak tidak ada jalan keluar dan menumbuhkan kebencian terhadap mereka yang memiliki lebih banyak (the have). Akibatnya, mati sebagai pahlawan (hero) sebagai ‘jalan keluar dari kemiskinan’ adalah menjadi pilihan terbaik.
Garis kebodohan dimana orang miskin tidak punya kesempatan atas pendidikan yang baik, juga mudah dimanipulasi oleh fenomena post-truth terkait prasangka yang penuh kebencian. Ketika kelompok radikal dan ekstrimis ini bisa mendekati kalangan ini, maka proses indoktrinasi untuk menjadi pasukan penebar teror akan lebih mudah.
Untuk membuktikan hipotesanya ini, Haroon Ullah tinggal di Pakistan dan melakukan riset serta hidup bersama dengan para tokoh ekstremis yang sedang mencari anggota baru. Ternyata dua hipotesa di atas yang terkait sumber terorisme berdasarkan kemiskinan karena kurang pangan dan kebodohan karena kurang bacaan belum tentu benar. Seperti halnya di Indonesia, kasus penjual bakso yang membuat bom panci dan rela mati untuk tujuan jihad, kenyataannya berasal dari kelas menengah dan mengenyam pendidikan tinggi. Jadi, apa yang mendorong calon pengantin mudah diindoktrinasi dan direkrut menjadi pengebom bunuh diri?
Paling tidak ada dua hal yang mengkondisikan hal tersebut. Pertama adalah keinginan seseorang akan makna hidup (meaning) dan ketentraman (world order). Banyak negara dunia ketiga seperti Pakistan berkubang dalam kekacauan (chaos) dan korupsi. Di negara tersebut, banyak pemuka agama yang menjanjikan solusi tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Caranya dengan mengindoktrinasi bahwa calon pengantin harus mengikuti ajaran agama Islam (post-truth) apabila ingin terjadi perubahan.
Kedua, adalah pengkondisian bahwa satu satunya jalan untuk menjawab kerinduan akan terjadinya perubahan adalah dengan menumbangkan pemerintahan yang legal tapi korup dan membuat pemerintahan baru yang bersih meski dengan jalan aksi kekerasan. Melalui proses post-truth, si calon pengantin seolah ‘menjadi korban kebijakan pemerintah” sehingga rela menjadi ‘pengantin’ untuk melawan antek pemerintah.
Menurut catatan sejarah, ternyata proses tersebut juga dilakukan oleh pemimpin dunia seperti Lenin, Mussolini, Hitler hingga Osama Bin Laden. Terkini, ISIS juga merekrut para pengikutnya untuk menjadi calon pengantin dengan cara yang sama. Haroon selanjutnya dalam disertasinya menawarkan solusi untuk mengatasi situasi tersebut. Yang pertama para pemangku kepentingan harus berhasil membuang narasi palsu (post-truth) ini bahwa alasan utama menjadi teroris adalah masalah kemiskinan dan pendidikan. Sedang yang kedua, mempelajari post-truth yang dibentuk oleh kelompok ekstrimis, bahwa janji surga dan kehidupan lebih baik sebagai bentuk hoax atau berita palsu dengan menghadirkan fakta bahwa teror bom lebih banyak membuat banyak kematian, kesengsaraan dan kemiskinan baru jika mereka berhasil melakukannya. (*)